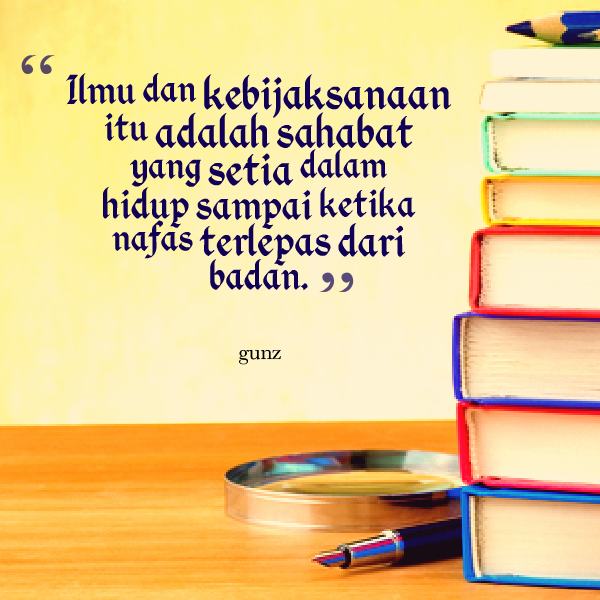-CikguAgus- Filsafat ilmu merupakan bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Bidang ini mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi dan implikasi dari ilmu, yang termasuk di dalamnya antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Di sini, filsafat ilmu sangat berkaitan erat dengan epistemologi dan ontologi. Filsafat ilmu berusaha untuk dapat menjelaskan masalah-masalah seperti: apa dan bagaimana suatu konsep dan pernyataan dapat disebut sebagai ilmiah, bagaimana konsep tersebut dilahirkan, bagaimana ilmu dapat menjelaskan, memperkirakan serta memanfaatkan alam melalui teknologi; cara menentukan validitas dari sebuah informasi; formulasi dan penggunaan metode ilmiah; macam-macam penalaran yang dapat digunakan untuk mendapatkan kesimpulan; serta implikasi metode dan model ilmiah terhadap masyarakat dan terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri.
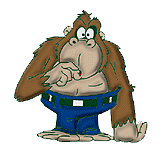 A. Konsep dan pernyataan ilmiah
A. Konsep dan pernyataan ilmiah
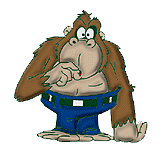 A. Konsep dan pernyataan ilmiah
A. Konsep dan pernyataan ilmiah
Ilmuberusaha menjelaskan tentang apa dan bagaimana alam sebenarnya dan bagaimana teori ilmu pengetahuan dapat menjelaskan fenomena yang terjadi di alam. Untuk tujuan ini, ilmu menggunakan bukti dari eksperimen, deduksi logis serta pemikiran rasional untuk mengamati alam dan individual di dalam suatu masyarakat.
1. Empirisme
Salah satu konsep mendasar tentang filsafat ilmu adalah empirisme, atau ketergantungan pada bukti. Empirisme adalah cara pandang bahwa ilmu pengetahuan diturunkan dari pengalaman yang kita alami selama hidup kita. Di sini, pernyataan ilmiah berarti harus berdasarkan dari pengamatan atau pengalaman. Hipotesa ilmiah dikembangkan dan diuji dengan metode empiris, melalui berbagai pengamatan dan eksperimentasi. Setelah pengamatan dan eksperimentasi ini dapat selalu diulang dan mendapatkan hasil yang konsisten, hasil ini dapat dianggap sebagai bukti yang dapat digunakan untuk mengembangkan teori-teori yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena alam.
2. Falsifiabilitas
Salah satu cara yang digunakan untuk membedakan antara ilmu dan bukan ilmu adalah konsep falsifiabilitas. Konsep ini digagas oleh Karl Popper pada tahun 1919-20 dan kemudian dikembangkan lagi pada tahun 1960-an. Prinsip dasar dari konsep ini adalah, sebuah pernyataan ilmiah harus memiliki metode yang jelas yang dapat digunakan untuk membantah atau menguji teori tersebut. Misalkan dengan mendefinisikan kejadian atau fenomena apa yang tidak mungkin terjadi jika pernyataan ilmiah tersebut memang benar.
- Pengertian Filsafat Ilmu
- Untuk memahami arti dan makna filsafat ilmu, di bawah ini dikemukakan pengertian filsafat ilmu dari beberapa ahli yang terangkum dalam Filsafat Ilmu, yang disusun oleh Ismaun (2001)
- Robert Ackerman “philosophy of science in one aspect as a critique of current scientific opinions by comparison to proven past views, but such aphilosophy of science is clearly not a discipline autonomous of actual scientific paractice”. (Filsafat ilmu dalam suatu segi adalah suatu tinjauan kritis tentang pendapat-pendapat ilmiah dewasa ini dengan perbandingan terhadap kriteria-kriteria yang dikembangkan dari pendapat-pendapat demikian itu, tetapi filsafat ilmu jelas bukan suatu kemandirian cabang ilmu dari praktek ilmiah secara aktual.
- Lewis White Beck “Philosophy of science questions and evaluates the methods of scientific thinking and tries to determine the value and significance of scientific enterprise as a whole. (Filsafat ilmu membahas dan mengevaluasi metode-metode pemikiran ilmiah serta mencoba menemukan dan pentingnya upaya ilmiah sebagai suatu keseluruhan)
- A. Cornelius Benjamin “That philosopic disipline which is the systematic study of the nature of science, especially of its methods, its concepts and presuppositions, and its place in the general scheme of intellectual discipines. (Cabang pengetahuan filsafati yang merupakan telaah sistematis mengenai ilmu, khususnya metode-metodenya, konsep-konsepnya dan praanggapan-praanggapan, serta letaknya dalam kerangka umum cabang-cabang pengetahuan intelektual.)
- Michael V. Berry “The study of the inner logic if scientific theories, and the relations between experiment and theory, i.e. of scientific methods”. (Penelaahan tentang logika interen dari teori-teori ilmiah dan hubungan-hubungan antara percobaan dan teori, yakni tentang metode ilmiah.)
- May Brodbeck “Philosophy of science is the ethically and philosophically neutral analysis, description, and clarifications of science.” (Analisis yang netral secara etis dan filsafati, pelukisan dan penjelasan mengenai landasan – landasan ilmu.
- Peter Caws “Philosophy of science is a part of philosophy, which attempts to do for science what philosophy in general does for the whole of human experience. Philosophy does two sorts of thing: on the other hand, it constructs theories about man and the universe, and offers them as grounds for belief and action; on the other, it examines critically everything that may be offered as a ground for belief or action, including its own theories, with a view to the elimination of inconsistency and error. (Filsafat ilmu merupakan suatu bagian filsafat, yang mencoba berbuat bagi ilmu apa yang filsafat seumumnya melakukan pada seluruh pengalaman manusia. Filsafat melakukan dua macam hal : di satu pihak, ini membangun teori-teori tentang manusia dan alam semesta, dan menyajikannya sebagai landasan-landasan bagi keyakinan dan tindakan; di lain pihak, filsafat memeriksa secara kritis segala hal yang dapat disajikan sebagai suatu landasan bagi keyakinan atau tindakan, termasuk teori-teorinya sendiri, dengan harapan pada penghapusan ketakajegan dan kesalahan
- Stephen R. Toulmin “As a discipline, the philosophy of science attempts, first, to elucidate the elements involved in the process of scientific inquiry observational procedures, patens of argument, methods of representation and calculation, metaphysical presuppositions, and so on and then to veluate the grounds of their validity from the points of view of formal logic, practical methodology and metaphysics”. (Sebagai suatu cabang ilmu, filsafat ilmu mencoba pertama-tama menjelaskan unsur-unsur yang terlibat dalam proses penyelidikan ilmiah prosedur-prosedur pengamatan, pola-pola perbinacangan, metode-metode penggantian dan perhitungan, pra-anggapan-pra-anggapan metafisis, dan seterusnya dan selanjutnya menilai landasan-landasan bagi kesalahannya dari sudut-sudut tinjauan logika formal, metodologi praktis, dan metafisika).
Berdasarkan pendapat di atas kita memperoleh gambaran bahwa filsafat ilmu merupakan telaah kefilsafatan yang ingin menjawab pertanyaan mengenai hakikat ilmu, yang ditinjau dari segi ontologis, epistemelogis maupun aksiologisnya. Dengan kata lain filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi (filsafat pengetahuan) yang secara spesifik mengakaji hakikat ilmu, seperti :
- Obyek apa yang ditelaah ilmu ? Bagaimana ujud yang hakiki dari obyek tersebut? Bagaimana hubungan antara obyek tadi dengan daya tangkap manusia yang membuahkan pengetahuan ? (Landasan ontologis)
- Bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu? Bagaimana prosedurnya? Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar mendakan pengetahuan yang benar? Apakah kriterianya? Apa yang disebut kebenaran itu? Adakah kriterianya? Cara/teknik/sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu? (Landasan epistemologis)
- Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Bagaimana penentuan obyek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral ? Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral/profesional ? (Landasan aksiologis). (Jujun S. Suriasumantri, 1982)
B. Fungsi Filsafat Ilmu
Filsafat ilmu merupakan salah satu cabang dari filsafat. Oleh karena itu, fungsi filsafat ilmu kiranya tidak bisa dilepaskan dari fungsi filsafat secara keseluruhan, yakni :
- Sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada.
- Mempertahankan, menunjang dan melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat lainnya.
- Memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup dan pandangan dunia.
- Memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan
- Menjadi sumber inspirasi dan pedoman untuk kehidupan dalam berbagai aspek kehidupan itu sendiri, seperti ekonomi, politik, hukum dan sebagainya. Disarikan dari Agraha Suhandi (1989)
Sedangkan Ismaun (2001) mengemukakan fungsi filsafat ilmu adalah untuk memberikan landasan filosofik dalam memahami berbagi konsep dan teori sesuatu disiplin ilmu dan membekali kemampuan untuk membangun teori ilmiah. Selanjutnya dikatakan pula, bahwa filsafat ilmu tumbuh dalam dua fungsi, yaitu: sebagai confirmatory theories yaitu berupaya mendekripsikan relasi normatif antara hipotesis dengan evidensi dan theory of explanation yakni berupaya menjelaskan berbagai fenomena kecil ataupun besar secara sederhana.
C.Substansi Filsafat Ilmu
Telaah tentang substansi Filsafat Ilmu, Ismaun (2001) memaparkannya dalam empat bagian, yaitu substansi yang berkenaan dengan: (1) fakta atau kenyataan, (2) kebenaran (truth), (3) konfirmasi dan (4) logika inferensi.
1.Fakta atau kenyataan
Fakta atau kenyataan memiliki pengertian yang beragam, bergantung dari sudut pandang filosofis yang melandasinya.
- Positivistik berpandangan bahwa sesuatu yang nyata bila ada korespondensi antara yang sensual satu dengan sensual lainnya.
- Fenomenologik memiliki dua arah perkembangan mengenai pengertian kenyataan ini. Pertama, menjurus ke arah teori korespondensi yaitu adanya korespondensi antara ide dengan fenomena. Kedua, menjurus ke arah koherensi moralitas, kesesuaian antara fenomena dengan sistem nilai.
- Rasionalistik menganggap suatu sebagai nyata, bila ada koherensi antara empirik dengan skema rasional, dan
- Realisme-metafisik berpendapat bahwa sesuatu yang nyata bila ada koherensi antara empiri dengan obyektif.
- Pragmatisme memiliki pandangan bahwa yang ada itu yang berfungsi.
Di sisi lain, Lorens Bagus (1996) memberikan penjelasan tentang fakta obyektif dan fakta ilmiah. Fakta obyektif yaitu peristiwa, fenomen atau bagian realitas yang merupakan obyek kegiatan atau pengetahuan praktis manusia. Sedangkan fakta ilmiah merupakan refleksi terhadap fakta obyektif dalam kesadaran manusia. Yang dimaksud refleksi adalah deskripsi fakta obyektif dalam bahasa tertentu. Fakta ilmiah merupakan dasar bagi bangunan teoritis. Tanpa fakta-fakta ini bangunan teoritis itu mustahil. Fakta ilmiah tidak terpisahkan dari bahasa yang diungkapkan dalam istilah-istilah dan kumpulan fakta ilmiah membentuk suatu deskripsi ilmiah.
2. Kebenaran (truth)
Sesungguhnya, terdapat berbagai teori tentang rumusan kebenaran. Namun secara tradisional, kita mengenal 3 teori kebenaran yaitu koherensi, korespondensi dan pragmatik (Jujun S. Suriasumantri, 1982). Sementara, Michel William mengenalkan 5 teori kebenaran dalam ilmu, yaitu : kebenaran koherensi, kebenaran korespondensi, kebenaran performatif, kebenaran pragmatik dan kebenaran proposisi. Bahkan, Noeng Muhadjir menambahkannya satu teori lagi yaitu kebenaran paradigmatik. (Ismaun; 2001)
a. Kebenaran koherensi
Kebenaran koherensi yaitu adanya kesesuaian atau keharmonisan antara sesuatu yang lain dengan sesuatu yang memiliki hirarki yang lebih tinggi dari sesuatu unsur tersebut, baik berupa skema, sistem, atau pun nilai. Koherensi ini bisa pada tatanan sensual rasional mau pun pada dataran transendental.
b.Kebenaran korespondensi
Berfikir benar korespondensial adalah berfikir tentang terbuktinya sesuatu itu relevan dengan sesuatu lain. Koresponsdensi relevan dibuktikan adanya kejadian sejalan atau berlawanan arah antara fakta dengan fakta yang diharapkan, antara fakta dengan belief yang diyakini, yang sifatnya spesifik
c.Kebenaran performatif
Ketika pemikiran manusia menyatukan segalanya dalam tampilan aktual dan menyatukan apapun yang ada dibaliknya, baik yang praktis yang teoritik, maupun yang filosofik, orang mengetengahkan kebenaran tampilan aktual. Sesuatu benar bila memang dapat diaktualkan dalam tindakan.
d.Kebenaran pragmatik
Yang benar adalah yang konkret, yang individual dan yang spesifik dan memiliki kegunaan praktis.
e.Kebenaran proposisi
Proposisi adalah suatu pernyataan yang berisi banyak konsep kompleks, yang merentang dari yang subyektif individual sampai yang obyektif. Suatu kebenaran dapat diperoleh bila proposisi-proposisinya benar. Dalam logika Aristoteles, proposisi benar adalah bila sesuai dengan persyaratan formal suatu proposisi. Pendapat lain yaitu dari Euclides, bahwa proposisi benar tidak dilihat dari benar formalnya, melainkan dilihat dari benar materialnya.
f.Kebenaran struktural paradigmatik
Sesungguhnya kebenaran struktural paradigmatik ini merupakan perkembangan dari kebenaran korespondensi. Sampai sekarang analisis regresi, analisis faktor, dan analisis statistik lanjut lainnya masih dimaknai pada korespondensi unsur satu dengan lainnya. Padahal semestinya keseluruhan struktural tata hubungan itu yang dimaknai, karena akan mampu memberi eksplanasi atau inferensi yang lebih menyeluruh.
3.Konfirmasi
Fungsi ilmu adalah menjelaskan, memprediksi proses dan produk yang akan datang, atau memberikan pemaknaan. Pemaknaan tersebut dapat ditampilkan sebagai konfirmasi absolut atau probalistik. Menampilkan konfirmasi absolut biasanya menggunakan asumsi, postulat, atau axioma yang sudah dipastikan benar. Tetapi tidak salah bila mengeksplisitkan asumsi dan postulatnya. Sedangkan untuk membuat penjelasan, prediksi atau pemaknaan untuk mengejar kepastian probabilistik dapat ditempuh secara induktif, deduktif, ataupun reflektif.
4.Logika inferensi
Logika inferensi yang berpengaruh lama sampai perempat akhir abad XX adalah logika matematika, yang menguasai positivisme. Positivistik menampilkan kebenaran korespondensi antara fakta. Fenomenologi Russel menampilkan korespondensi antara yang dipercaya dengan fakta. Belief pada Russel memang memuat moral, tapi masih bersifat spesifik, belum ada skema moral yang jelas, tidak general sehingga inferensi penelitian berupa kesimpulan kasus atau kesimpulan ideografik.
Post-positivistik dan rasionalistik menampilkan kebenaran koheren antara rasional, koheren antara fakta dengan skema rasio, Fenomena Bogdan dan Guba menampilkan kebenaran koherensi antara fakta dengan skema moral. Realisme metafisik Popper menampilkan kebenaran struktural paradigmatik rasional universal dan Noeng Muhadjir mengenalkan realisme metafisik dengan menampilkan kebenaranan struktural paradigmatik moral transensden. (Ismaun,200:9)
Di lain pihak, Jujun Suriasumantri (1982:46-49) menjelaskan bahwa penarikan kesimpulan baru dianggap sahih kalau penarikan kesimpulan tersebut dilakukan menurut cara tertentu, yakni berdasarkan logika. Secara garis besarnya, logika terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu logika induksi dan logika deduksi.
D. Corak dan Ragam Filsafat Ilmu
Ismaun (2001:1) mengungkapkan beberapa corak ragam filsafat ilmu, diantaranya:
- Filsafat ilmu-ilmu sosial yang berkembang dalam tiga ragam, yaitu : (1) meta ideologi, (2) meta fisik dan (3) metodologi disiplin ilmu.
- Filsafat teknologi yang bergeser dari C-E (conditions-Ends) menjadi means. Teknologi bukan lagi dilihat sebagai ends, melainkan sebagai kepanjangan ide manusia.
- Filsafat seni/estetika mutakhir menempatkan produk seni atau keindahan sebagai salah satu tri-partit, yakni kebudayaan, produk domain kognitif dan produk alasan praktis.
Produk domain kognitif murni tampil memenuhi kriteria: nyata, benar, dan logis. Bila etik dimasukkan, maka perlu ditambah koheren dengan moral. Produk alasan praktis tampil memenuhi kriteria oprasional, efisien dan produktif. Bila etik dimasukkan perlu ditambah human.manusiawi, tidak mengeksploitasi orang lain, atau lebih diekstensikan lagi menjadi tidak merusak lingkungan.
id.wikipedia/wiki/filsafat ilmu
http./aljawad.tripod.com/artikel/filsafat _ilmu.htm
www.te.ugm.ac.id







 08.47
08.47
 Agus Rahmaddi
Agus Rahmaddi